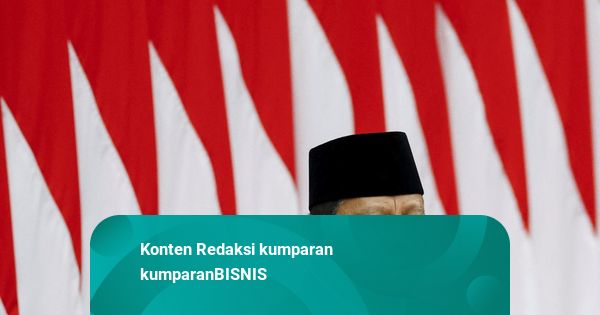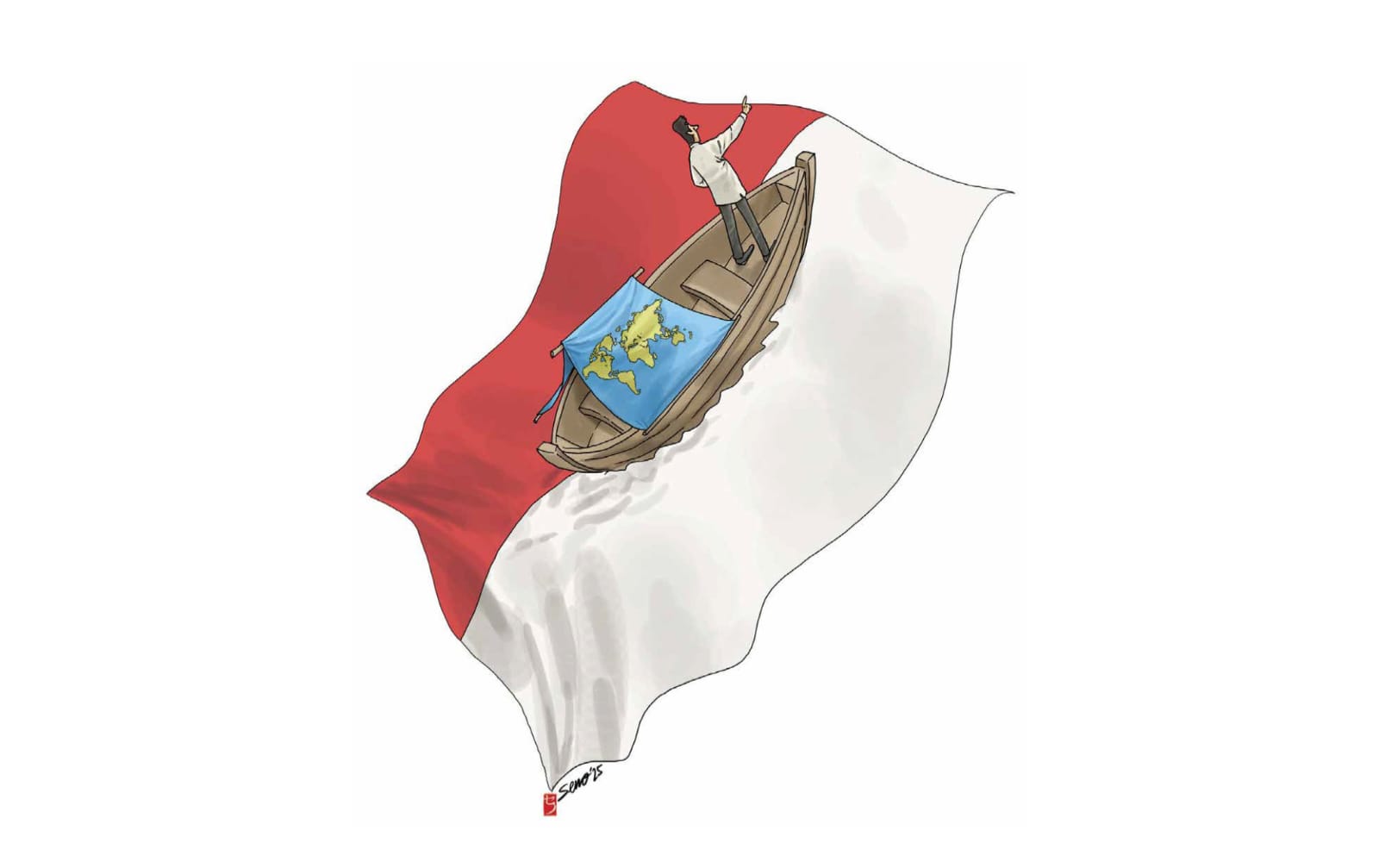 (MI/Seno)
(MI/Seno)
DELAPAN puluh tahun ialah usia yang tidak muda bagi sebuah bangsa, tapi juga tak dapat dikatakan tua. Ia fase ketika sejarah dan masa depan saling menatap dalam cermin waktu. Saat sang Saka Merah Putih pertama kali berkibar di Pegangsaan Timur pada 17 Agustus 1945, kemerdekaan hadir sebagai janji, bukan jawaban. Janji bahwa bangsa Indonesia akan bebas menentukan nasibnya, tidak hanya dari penjajahan fisik, tetapi juga dari segala bentuk ketergantungan yang melumpuhkan.
Hari ini, janji itu kembali diuji. Dunia telah berubah menjadi jaringan saraf raksasa, tempat setiap keputusan di satu belahan bumi dapat mengguncang sendi ekonomi di belahan lain. Kemerdekaan kini tidak lagi sebatas menolak penjajahan kolonial, tetapi kemampuan menegosiasikan nasib di ruang global yang penuh paradoks.
Dalam lanskap rapuh tetapi kaya peluang ini, adagium klasik pun bergaung kembali: seribu teman terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Diplomasi ekonomi menjadi panggung tempat Indonesia menguji makna kemerdekaan: bukan hanya bertahan, melainkan juga memperluas ruang hidup melalui pertemanan, perundingan, dan keberanian.
Kemerdekaan, karenanya, ialah proses, seperti air yang mengalir dari hulu ke muara, menabrak tebing, lalu menemukan jalannya sendiri. HOS Tjokroaminoto pernah mengajarkan gagasan zelfbestuur, pemerintahan mandiri, sebagai inti perjuangan politik. Kini, makna itu berkembang: kedaulatan tidak cukup dimaknai sebagai kebebasan dari penjajah, tetapi juga kemampuan menegakkan otoritas dalam arus globalisasi.
Selama beberapa dekade, makna itu sempat digeser narasi yang meminggirkan peran negara. Pidato inaugurasi Ronald Reagan pada 1981, yang menyebut pemerintah sebagai masalah, melahirkan paradigma global yang menyingkirkan negara dari ruang pembangunan. Kebebasan ekonomi tanpa kendali melahirkan ketimpangan, sebagaimana dikritik Thomas Piketty dan Jeffrey Sachs, kemakmuran yang dibangun, tetapi lupa membayar ongkos peradaban.
Di sinilah gagasan zelfbestuur menemukan relevansinya kembali: negara bukan penghalang, melainkan napas pembangunan. Amartya Sen menyebutnya development as freedom, pembangunan sebagai jalan menuju kebebasan, dengan tiap individu memperoleh akses setara pada kesempatan.
Dengan kerangka itu, diplomasi ekonomi menjadi wujud konkret zelfbestuur di era modern. Jika dulu zelfbestuur berarti bebas dari belenggu penjajah, kini ia berarti berdaulat di tengah arus globalisasi. Pemerintah dituntut tidak hanya mengelola sumber daya dalam negeri, tetapi juga piawai menavigasi dinamika eksternal yang kerap tak terduga. Kemerdekaan menjadi lensa ganda: mengakar kuat di tanah sendiri, sekaligus menjalin simpul dalam jejaring dunia.
DIPLOMASI BILATERAL
Dalam dunia yang multipolar, diplomasi bilateral sering kali menyerupai titian bambu: lentur, tipis, dan mudah terguncang jika langkahnya salah. Negosiasi tarif dengan Amerika Serikat ialah bukti nyata. Di tengah derasnya arus proteksionisme, Indonesia tidak bisa sekadar menerima kenyataan. Pemerintah berunding, menimbang untung rugi, dan akhirnya berhasil menekan tarif hingga 19%, jauh lebih rendah dari ancaman awal 32%.
Namun, angka itu bukan sekadar hitungan dagang. Ia simbol kedaulatan: Indonesia tidak tunduk, tetapi juga tidak menutup pintu. Kita tetap hadir di pasar global meski dengan ongkos kompromi. Inilah seni diplomasi: menolak kalah, sekaligus menghindari musuh.
Hal serupa tampak dalam diskusi ekonomi dengan Prancis. Eropa, khususnya Prancis, ialah pintu bagi peluang masa depan, energi hijau, teknologi digital, hingga pasar berstandar tinggi. Melalui percakapan itu, Indonesia memperkuat simpul, membuka akses baru, dan memastikan kita tidak hanya menjual bahan mentah, tetapi juga gagasan dan produk bernilai tambah. Bilateral, dengan demikian, tidak sekadar menjaga hubungan, tetapi juga mengukir jalan baru menuju kemandirian.
Jika bilateral ialah titian rapuh, multilateral ialah pilar baja. Forum-forum seperti ASEAN, G-20, hingga RCEP menjadi wadah Indonesia tidak sekadar ikut, tetapi turut menggerakkan.
RCEP, misalnya, ialah manifestasi dari sila-sila Pancasila dalam praktik perdagangan. Prinsip 'kemanusiaan yang adil dan beradab' terlihat dalam aturan mobilitas pekerja yang lebih setara. 'Persatuan Indonesia' menemukan gaungnya dalam semangat regionalisme yang menghapus sekat imajiner antarbangsa.
Bahkan sila kelima, 'keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia', mewujud dalam harapan bahwa konvergensi ekonomi di kawasan akan menekan ketimpangan antarnegara.
Di sisi lain, negosiasi Indonesia–EU CEPA menjadi contoh diplomasi bikameral. Indonesia berunding keras di meja bilateral, tetapi juga menjaga keseimbangan dalam kerangka multilateral. CEPA bukan hanya soal tarif; ia juga soal regulasi lingkungan, standar ketenagakerjaan, dan hak kekayaan intelektual. Jika dinegosiasikan dengan cermat, CEPA bisa membuka peluang ekspor bernilai tinggi, bukan sekadar komoditas mentah. Jika tidak, ia bisa menjadi jebakan yang mengekang. Di sinilah ketelitian diplomasi kita diuji.
EKONOMI PANCASILA
Dalam forum internasional, Presiden Prabowo menegaskan arah ekonomi Indonesia: ekonomi Pancasila. Ia jalan tengah antara kapitalisme yang subur, tetapi timpang, dan sosialisme yang merata, tetapi stagnan. Jalan tengah itu menempatkan pemerintah bukan sebagai pengendali absolut, tetapi juga bukan penonton pasif.
Ekonomi Pancasila menjadi strategi kebijakan luar negeri: membuka pintu bagi investasi global, tetapi menjaga kendali domestik agar kedaulatan tidak tergadaikan. Diplomasi ekonomi, dalam kerangka itu, bukan sekadar mengejar pertumbuhan, melainkan juga memastikan hasil pertumbuhan menyentuh seluruh lapisan rakyat. Seperti Amartya Sen mengingatkan, pembangunan sejati ialah development as freedom, kebebasan ekonomi yang hanya bermakna jika ada akses dan kesetaraan.
Namun, semua manuver diplomasi akan hampa jika rumah dalam negeri rapuh. Produktivitas tenaga kerja Indonesia stagnan sehingga upah kita terlihat mahal tanpa daya saing riil, menimbulkan risiko investment diversionp> ke negara tetangga.
Inilah peringatan Acemoglu dan Robinson: tanpa institusi inklusif, negara hanya melayani segelintir elite. Bonus demografi yang kita miliki ialah jendela peluang yang sempit. Jika momentum itu lewat, kita akan menjadi tua sebelum kaya.
Dengan demikian, diplomasi internasional harus bersinergi dengan reformasi domestik: memperbaiki pendidikan, meningkatkan produktivitas, dan membuka ruang usaha seluas-luasnya. Tanpa itu, keuntungan dari perjanjian internasional hanya akan berputar di lingkaran elite, sementara rakyat tetap menonton dari pinggir.
Delapan puluh tahun merdeka, Indonesia harus berani menatap dunia dengan kepala tegak. Bilateral dan multilateral bukanlah dua jalur yang saling meniadakan, melainkan dua sayap yang membuat 'Garuda' terbang lebih tinggi. Satu sayap menjaga sahabat dekat, sayap lain merangkul dunia. Keduanya memastikan kita tidak terjebak dalam isolasi, tetapi juga tidak hanyut dalam arus global tanpa arah.
KEMERDEKAAN YANG SEJATI
Kemerdekaan yang sejati bukan sekadar bendera yang berkibar setiap Agustus. Ia adalah rakyat yang berdaya, pekerja yang sejahtera, dan generasi muda yang memiliki harapan. Diplomasi ekonomi, dalam pengertian itu, ialah napas baru dari kemerdekaan itu sendiri. Apa arti merdeka jika kita tidak mampu menegosiasikan masa depan kita di meja dunia?
Indonesia, delapan puluh tahun berdiri, kini menapaki babak baru: dari bangsa yang pernah dijajah menjadi bangsa yang menentukan. Dalam perjalanan itu, kita belajar satu hal penting: kemerdekaan yang memerdekakan hanya bisa diraih dengan keberanian membuka diri, kebijaksanaan menjaga kedaulatan.

 5 hours ago
4
5 hours ago
4